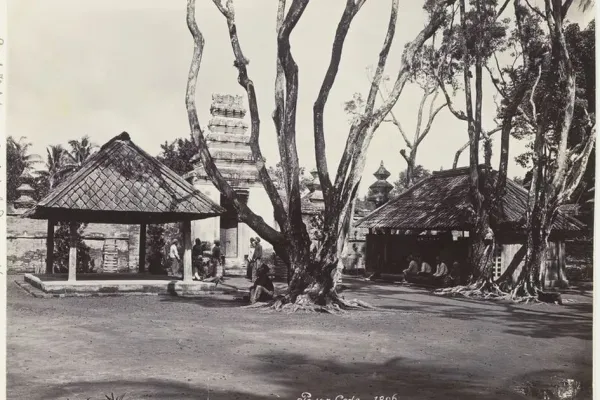
Tak hanya dua, Mataram Islam pecah jadi empat: Kasunanan Surakarta, Kesultanan Yogyakarta, Kadipaten Mangkunegaran, dan Kadipaten Pakualaman.
---
Intisari hadir di whatsapp channel, follow dan dapatkan berita terbaru kami di sini
---
Intisari-Online.com -Tak hanya jadi dua, Mataram Islam nyatanya pecah jadi empat. Selain Kasunanann Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta, pecahan Mataram Islam juga meliputi Kadipaten Mangkunegaran dan Kadipaten Pakualaman.
Tapi secara garis besar, setidaknya ada tiga goncangan besar yang terjadi di masa Mataram Islam. Periode-periode itu, kelak di kemudian hari dikenal sebagai Perang Takhta Jawa I, Perang Takhta Jawa II, dan Perang Takhta III.
Di dua perang suksesi pertama Mataram Islam memang tergoncang. Tapi kerajaan yang didirikan oleh Panembahan Senopati itu masih tetap utuh.
Hingga kemudian terjadilah perang suksesi ketiga di mana Mataram Islam akhirnya merasakan dampaknya secara signifikan. Awalnya, Mataram Islam pecah jadi dua: Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta.
Perpecahan itu ditandai dengan ditandatanganinya Perjanjian Giyanti pada 1755. Tak berhenti di situ, menyusul kemudia lahirlah Kadipaten Mangkunegaraan pada 1757 dan Kadipaten Pakualaman pada 1813.
Semua berawal dari peristiwa Geger Pecinan pada 1742. Pemberontakan itu mengakibatkan ibu kota Kerajaan Mataram Islam di Kartasura hancur. Peristiwa tersebut melibatkan salah satu pangeran Mataram, yakni Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa, keponakan Pakubuwono II.
Karena Keraton Kartasura hancur, Pakubuwono II (1726-1749) memindahkan ibu kota kerajaan ke Keraton Surakarta. Pemerintahan Pakubuwono II dapat bertahan selama lebih dari dua dekade tidak lepas dari peran VOC.
Karena itu pula, intrik di kalangan para bangsawan Mataram terus terjadi dan Pakubuwono II semakin diperas oleh VOC. Salah satu penyebab Perang Takhta Jawa III adalah kekesalan Pangeran Mangkubumi, adik Pakubuwono II, terhadap sikap VOC.
Suatu hari, Gubernur Jenderal VOC Baron van Imhoff datang untuk mendesak Pakubuwono II agar menyewakan daerah pesisir kepada VOC dengan harga cukup murah per tahun. Permintaan itu ditentang oleh Pangeran Mangkubumi.
Karena hal itu, Baron van Imhoff menghina Pangeran Mangkubumi dan memengaruhi Pakubuwono II untuk membatalkan pemberian tanah di Sukawati (sekarang Sragen) yang telah dijanjikan. Pangeran Mangkubumi pun sakit hati.
Dia memilih meninggalkan Keraton Surakarta untuk bergabung bersama Raden Mas Said. Itulah penyebab meletusnya perang saudara di Kerajaan Mataram Islam yang kemudian disebut sebagai Perang Suksesi Jawa III, antara Pakubuwono II melawan Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said.
Di tengah perlawanan Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said, Pakubuwono II meninggal pada 20 Desember 1749. Sebelum meninggal, Pakubuwono II sempat menandatangani perjanjian dengan VOC, yang oleh para sejarawan disebut sebagai titik awal hilangnya Kerajaan Mataram Islam.
Putra Pakubuwono II, Raden Mas Suryadi, kemudian dinobatkan sebagai raja bergelar Pakubuwono III. Pakubuwono III meneruskan Perang Takhta Jawa III melawan Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said dibantu VOC.
Pada 1752, terjadi perpecahan antara Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said. Hal itu segera dimanfaatkan oleh VOC, yang mengirimkan Nicolas Hartingh untuk menawarkan perdamaian kepada Pangeran Mangkubumi.
VOC berhasil menarik Pangeran Mangkubumi untuk menghadiri Perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755. Perjanjian Giyanti secara resmi membagi Kesultanan Mataram menjadi dua.
Bagian timur Mataram menjadi milik Pakubuwono III, dengan tetap berkedudukan di Keraton Surakarta, sementara bagian barat Mataram diberikan kepada Pangeran Mangkubumi. Pangeran Mangkubumi kemudian mendirikan Kasultanan Yogyakarta dan memerintah dengan gelar Sultan Hamengkubuwono I.
Dengan kata lain, Perjanjian Giyanti melahirkan Nagari Kasunanan Surakarta yang diperintah oleh Sunan Pakubuwono III dan Kasultanan Ngayogyakarta dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwono I.
Raden Mas Said, yang tidak ikut dalam Perjanjian Giyanti masih gencar melakukan perlawanan. VOC berulang kali menawarkan solusi dengan jalan perundingan, yang akhirnya diterima oleh Raden Mas Said.
Pihak-pihak terkait kemudian berkumpul di Salatiga, Jawa Tengah, pada 17 Maret 1757 untuk menyepakati Perjanjian Salatiga. Dalam perjanjian itu, Raden Mas Said diakui sebagai pangeran merdeka dengan wilayah otonom berstatus kadipaten yang disebut Praja Mangkunegaran.
Perjanjian Salatiga menandai berdirinya Praja Mangkunegaran, kadipaten yang posisinya di bawah kasunanan dan kasultanan. Sehingga penguasanya tidak berhak menyandang gelar Sunan ataupun Sultan.
Gelar para penguasa yang memegang pemerintahan di Mangkunegaran adalah Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya (KGPAA). Raden Mas Said kemudian dinobatkan sebagai pendiri sekaligus penguasa pertama Mangkunegaran yang bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara I.
Kedudukan Mangkunegara berada di Pura Mangkunegaran, yang didirikan di kawasan yang sekarang masuk wilayah Banjarsari, Surakarta, tidak jauh dari Keraton Surakarta.
Perjanjian Salatiga menandai bahwa Kesultanan Mataram telah terbagi menjadi tiga kekuasaan yang diperintah oleh Hamengkubuwono I, Pakubuwono III, dan Mangkunegara I. Terbaginya Kerajaan Mataram Islam menjadi tiga menandai akhir dari Perang Takhta Jawa III.
Tapi itu ternyata bukan akhir dari rebutan kekuasan Trah Mataram, karena sekitar 50 tahun kemudian berdiri Kadipaten Pakualaman di Yogyakarta. Kadipaten Pakualaman adalah pecahan Kesultanan Yogyakarta yang dibentuk berdasarkan kontrak politik antara pemerintah Penjajah Inggris dengan Pangeran Notokusumo, yang merupakan putra Sultan Hamengkubuwono I dari selirnya yang bernama Raden Ayu Srenggorowati.
Status praja atau Kadipaten Pakualaman mirip dengan Praja Mangkunegaran di Surakarta. Dengan pembentukan Pakualaman pada 1813, Kesultanan Mataram resmi terpecah menjadi empat kekuasaan.
Awalnya pada 1808, ketika Herman Willem Daendels diangkat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Kebijakan Daendels ternyata mendapatkan tentangan dari Sultan Hamengkubuwono II, yang saat itu bertakhta di Kasultanan Yogyakarta.
Karena itu HB II dilengserkan oleh Belanda. Daendels lalu mengangkat GRM Soerojo sebagai raja baru bergelar Sultan Hamengkubuwono III. Sedangkan saudara tiri Hamengkubuwono II, Pangeran Notokusumo, yang juga ikut menentang Daendels, ditangkap dan dibawa ke Batavia.
Pada 1811, ketika kekuasaan kolonial Belanda di Pulau Jawa direbut oleh Inggris, Thomas Stamford Raffles dikirim untuk menjabat sebagai Gubernur Jenderal Britania Raya di Jawa. Untuk mendapatkan dukungan penguasa lokal, Raffles kemudian membebaskan Pangeran Notokusumo dan berjanji akan mengembalikan Hamengkubuwono II ke posisinya sebagai sultan. Hamengkubuwono III sendiri akan diturunkan kembali statusnya menjadi putra mahkota.
Tawaran Inggris itu diikuti dengan beberapa syarat yang merugikan Keraton Yogyakarta. Salah satu syarat yang ditolak oleh Sultan Hamengkubuwono II adalah pembubaran prajurit keraton.
Bahkan Sultan berencana menyerang Inggris. Namun, rencana itu dibocorkan oleh Pangeran Notokusumo kepada Inggris, sehingga meletus pertempuran berdarah pada Juni 1812, yang kemudian dikenal sebagai peristiwa Geger Sepehi.
Hasil dari pertempuran itu Hamengkubuwono II ditangkap dan diasingkan ke Ambon. Sebagai penggantinya, pemerintah Inggris mengembalikan Hamengkubuwono III ke singgasana keraton.
Atas jasanya membantu Inggris, pada 29 Juni 1812 Pangeran Notokusumo dinobatkan sebagai Pangeran Mardiko atau pangeran yang merdeka di dalam Keraton Yogyakarta, dengan gelar Paku Alam I.
Menyusul penobatannya sebagai Pangeran Mardiko, Pangeran Notokusumo menyepakati kontrak politik dengan pemerintah Inggris pada 17 Maret 1813. Penandatanganan kesepakatan tersebut menandai berdirinya Praja Pakualaman.
Beberapa hal penting dalam kontrak tersebut di antaranya.
1. Pemerintah Inggris memberi perlindungan langsung kepada Paku Alam dan keluarganya.
2. Inggris mengusahakan agar Sultan Hamengkubuwono III memberikan tanah kepada Paku Alam sebesar 4.000 cacah, yang meliputi area khusus di dalam Kota Yogyakarta dan kawasan yang disebut Adikarto (sekarang terletak di Kabupaten Kulon Progo bagian selatan).
3. Inggris memberikan 100 pasukan, lengkap dengan seragam dan persenjataannya, serta hak memungut pajak.
Dengan berlakuknya kontrak politik ini, Praja Pakualaman resmi menjadi nama monarki terkecil di Jawa Tengah bagian selatan. Sebagai swapraja, Kadipaten Pakualaman diberi hak otonom, yakni daerah yang mencakup dalam Kota Yogyakarta dan wilayah-wilayah Adikarto, di daerah selatan Kulon Progo yang meliputi Temon, Wates, Panjatan, Gakur, dan Lendah.
Praja Pakualaman juga dilengkapi dengan sebuah legiun, tetapi tidak untuk bertempur. Fungsinya hanya sebagai seremonial dan pengawal pejabat kadipaten.
Pada 7 Maret 1822, pemerintah kolonial Hindia Belanda memberi gelar Paku Alam I, Pangeran Adipati. Sedangkan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo (KGPAA) Paku Alam II baru diberikan oleh pemerintah kolonial setelah ditandatangani kontrak politik lainnya.
Pemerintahan dijalankan oleh Pepatih Pakualaman bersama residen atau Gubernur Hindia Belanda untuk Yogyakarta.
Meski begitu, status Praja Pakualaman beberapa kali berganti seiring dengan perjalanan waktu. Misalnya antara 1813-1816, statusnya sebagai negara dependen di bawah Pemerintah Kerajaan Inggris India Timur (East Indian).
Lalu antara 1816-1942, status Pakualaman adalah sebagai negara dependen Kerajaan Nederland, dengan status Zelfbestuurende Landschappen Hindia Belanda. Kemudian antara 1942-1945 menjadi bagian dari Kekaisaran Jepang dengan status Kooti di bawah pengawasan Penguasa Militer Tentara XVI Angkatan Darat. Dan terakhir, berasma Kasultanan Yogyakarta menjadi daerah istimewa.
Begitulah riwayat Mataram Islam, dari kesultanan yang begitu kuat akhirnya pecah jadi empat.