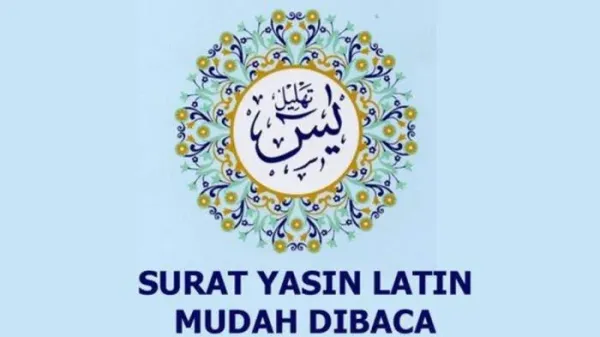Selama jurnalis tetap menyalakan terang di tengah gelap, demokrasi Indonesia akan terus bernapas
Semarang (ANTARA) - Indonesia memiliki Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, sebuah tonggak reformasi yang lahir dari semangat pembebasan. Regulasi ini bukan sekadar dokumen hukum, melainkan simbol komitmen bangsa terhadap kebebasan berekspresi dan transparansi publik.
Regulasi itu juga menjadi penegas bahwa pers berperan sebagai pilar keempat demokrasi.
Lebih dari dua dekade setelah undang-undang tersebut dilahirkan, tantangan terhadap kebebasan pers masih saja ada. Namun, di balik tantangan itu, tumbuh pula harapan, solidaritas, dan dorongan untuk memperkuat demokrasi.
Jurnalis adalah sosok yang tetap bertahan di garis depan, menjalankan tugasnya untuk menggali kebenaran, menyampaikan fakta, dan menjadi penghubung antara rakyat dan pengambil kebijakan di tengah dinamika sosial dan politik yang terjadi.
Semangat untuk menyampaikan informasi kepada publik tidak pernah padam dalam dada komitmen wartawan, meski seringkali mereka dihadapkan pada situasi yang tidak menguntungkan.
Dalam aksi massa yang terjadi belakangan ini misalnya, terjadi beberapa insiden kekerasan terhadap jurnalis. Pewarta foto ANTARA Bayu Pratama Syahputra mengalami kekerasan ketika meliput demonstrasi di gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Senayan, Jakarta, pada Senin (25/8), meski ia sudah mengenakan atribut peliputan lengkap seperti helm bertuliskan Pers ANTARA dan membawa dua kamera profesional.
Kemudian dua jurnalis foto dari Tempo dan ANTARA dipukul orang tidak dikenal saat meliput demonstrasi di sekitar Mako Brimob, Kwitang, Jakarta Pusat, pada Kamis (28/8) malam.
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mencatat selama 1 Januari hingga 31 Agustus 2025 ada 60 kasus kekerasan terhadap jurnalis dan media, termasuk teror, intimidasi dan serangan digital ke website dan akun media sosial media.
Pada Maret, jurnalis Tempo Francisca Christy Rosana menerima teror berupa kepala babi busuk dan bangkai tikus terpenggal yang dikirim ke rumah dan kantor redaksinya.
Namun alih-alih memadamkan api semangat, insiden-insiden ini justru memicu solidaritas lintas redaksi dan mendorong publik untuk lebih peduli terhadap perlindungan jurnalis. Di balik angka-angka itu, ada gerakan yang terus menguat: pelatihan keselamatan liputan, advokasi hukum, dan kampanye publik untuk menghormati kerja jurnalistik. Semakin banyak masyarakat yang menyadari bahwa jurnalis bukan ancaman, melainkan penjaga akal sehat bangsa.
Ruang bicara
Kritik terhadap pejabat atau proyek publik seharusnya dipandang sebagai bagian dari kontrol demokratis, bukan kejahatan.
Dalam sistem yang sehat, suara jurnalis adalah suara rakyat. Tanpa jurnalis yang bebas, rakyat kehilangan akses terhadap informasi kritis. Skandal korupsi bisa tertutup, pelanggaran HAM bisa terhapus dari ingatan kolektif, dan kebijakan publik bisa melenggang tanpa kontrol.
Tantangan yang masih kita hadapi adalah UU Pers, meski sudah menjamin kemerdekaan, dalam praktik di lapangan sering bertabrakan dengan pasal-pasal dalam KUHP dan UU ITE.
Meski demikian, diskusi publik tentang revisi regulasi kini semakin terbuka. Banyak akademisi, praktisi hukum, dan organisasi masyarakat sipil yang mendorong agar hukum lebih berpihak pada kebebasan berekspresi.
Contoh kasus di Sumbawa, di mana seorang jurnalis ditetapkan sebagai tersangka karena unggahan kritis, telah memicu diskusi nasional tentang batasan hukum dan perlindungan terhadap kebebasan pers. Ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak lagi diam. Mereka mulai bersuara, menuntut keadilan, dan mendukung jurnalis yang bekerja dengan integritas.
Ekosistem pers yang sehat
Tantangan tidak hanya datang dari regulasi, tetapi juga dari praktik birokrasi. Peraturan Polri Nomor 3 Tahun 2025 yang memperketat izin kerja jurnalis asing, misalnya, menimbulkan kekhawatiran bahwa liputan independen akan makin sulit dilakukan.
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menjelaskan bahwa Perpol ini dibuat sebagai bagian dari upaya preemptif dan preventif Polri dalam memberikan perlindungan serta pelayanan kepada warga negara asing (WNA), termasuk jurnalis yang bertugas di Indonesia.
Surat Keterangan Kepolisian (SKK), kata Kapolri, hanya diperuntukkan bagi jurnalis asing yang membutuhkan dokumen tersebut untuk bertugas di wilayah dengan potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), seperti Papua.
Ada sejumlah langkah positif yang bisa ditempuh untuk menciptakan ekosistem pers yang sehat. Di antaranya adalah penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan terhadap jurnalis yang dilakukan secara transparan dan tegas.
Selain itu, pasal-pasal karet dalam KUHP dan UU ITE perlu segera direvisi dan diperjelas agar tidak lagi digunakan sebagai alat untuk membungkam kritik. Perlindungan struktural juga harus diperkuat, di mana Dewan Pers tidak cukup hanya berperan sebagai lembaga sertifikasi, melainkan menjadi pelindung nyata bagi jurnalis di lapangan.
Pada saat yang sama, budaya politik yang sehat harus dibangun dengan kesadaran bahwa kritik bukanlah penghinaan dan liputan kritis bukanlah sabotase, sebab tanpa pemahaman ini demokrasi hanya akan menjadi jargon kosong.
Yang tak kalah penting, publik harus terus bersuara. Ketika masyarakat mendukung jurnalis, maka ruang demokrasi akan tetap hidup. Setiap berita yang ditulis dengan keberanian adalah sumbangan bagi sejarah bangsa.
Indonesia bukan tanpa harapan. Di tengah tantangan, ada ribuan jurnalis yang tetap bekerja dengan dedikasi. Itu adalah optimismes yang tak pernah padam.
Ada masyarakat yang mulai sadar bahwa informasi adalah hak, bukan kemewahan. Ada generasi muda yang belajar bahwa keberanian menulis adalah bentuk cinta terhadap negeri.
UU Pers bukan sekadar warisan reformasi. Ia adalah janji bahwa suara rakyat akan selalu punya ruang. Dan selama jurnalis tetap menyalakan terang di tengah gelap, demokrasi Indonesia akan terus bernapas.