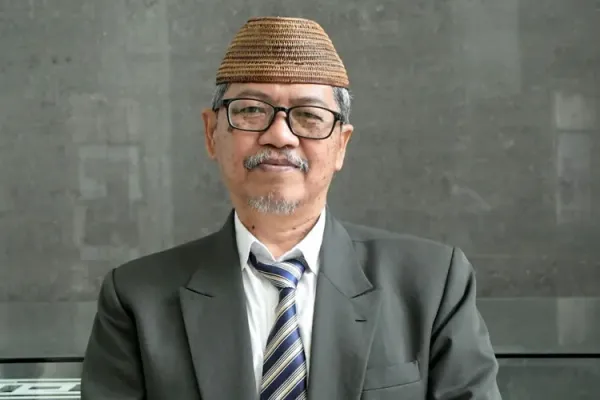
TIMESINDONESIA, MALANG – Ayat yang menjelaskan bahwa puasa dapat mengembalikan manusia pada kemanusiaan sejatinya (kefitriannya) adalah QS. Al-Baqarah (2): 185: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ . Ketaqwaan merupakan intisari dari jati diri kemanusiaan, sebagaimana ayat QS. Ar-Rum: 30 فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Ayat ini menegaskan bahwa manusia diciptakan dalam keadaan fitrah, yaitu kecenderungan alami untuk bertauhid dan menyembah Allah. Allah memerintahkan agar manusia menghadapkan dirinya dengan lurus kepada agama-Nya, yaitu Islam, yang merupakan ajaran yang sesuai dengan fitrah penciptaannya.
Kataحَنِيفًا "hanīfan" dalam ayat ini menunjukkan bahwa agama yang benar adalah agama yang lurus, tanpa penyimpangan menuju kemusyrikan atau kesesatan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari (No. 1358) dan Muslim (No. 2658), Rasulullah saw bersabda, كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ، هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ . Hadis ini menjelaskan bahwa setiap manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah, yaitu dalam keadaan suci dan memiliki kecenderungan alami untuk bertauhid kepada Allah. Namun, orang tuanya atau lingkungannya yang kemudian membentuk dan mengubah keyakinannya, menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi.
Bagian terakhir dari hadis ini "كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ، هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ" bermakna perumpamaan yang diberikan Rasulullah saw. "الْبَهِيمَةُ" (hewan ternak) lahir dalam keadaan sempurna, tanpa cacat. Hewan tidak dilahirkan dengan kondisi tertentu seperti cacat atau terpotong telinganya (جَدْعَاءَ berarti terpotong bagian telinganya), tetapi manusialah yang mengubahnya. Ini adalah analogi bahwa manusia lahir dalam keadaan fitrah, namun pengaruh luar yang mengubahnya dari keadaan fitrah tersebut.
Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam "Fathul Bari" (Jilid 3, 248) menjelaskan bahwa kata "fitrah" dalam hadis ini merujuk kepada Islam. Artinya, manusia sejak lahir memiliki kesiapan untuk mengenal Allah, tetapi lingkungan dan pendidikan yang diberikan oleh orang tuanya bisa mengubahnya. Pendapat ini diperkuat dengan ayat QS. Ar-Rum: 30, yang menyebutkan bahwa fitrah manusia adalah fitrah Allah, yaitu tauhid. Imam An-Nawawi dalam "Syarh Shahih Muslim" (Jilid 16, hal. 208-209) menjelaskan bahwa fitrah dalam hadis ini tidak berarti bahwa semua bayi otomatis Muslim, tetapi memiliki potensi untuk menerima Islam dan mengenal Allah. Jika anak tersebut dibiarkan tanpa pengaruh luar, maka ia akan tetap dalam keadaan fitrah, yaitu bertauhid kepada Allah.
Ayat yang menyatakan "tidak ada perubahan pada ciptaan Allah", berarti bahwa hukum Allah tidak akan berubah, dan fitrah manusia akan selalu cenderung kepada tauhid. Namun, secara sunnatullah manusia bisa merubah dirinya atau orang lain jauh dari kefitriannya tersebut, baik karena pengaruh hawa nafsu, budaya, maupun ketidaktahuannya. Oleh sebab itu, Ibnu Katsir dalam Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim, (jilid 6, 320-321) menjelaskan bahwa ayat ini merupakan perintah agar manusia tetap berpegang teguh pada Islam sebagai satu-satunya agama yang benar. Demikian pula dalam Tafsir Al-Qurtubi, Jami' li Ahkam al-Qur'an (jilid 14, 32-33) disebutkan bahwa fitrah di sini bermakna penciptaan manusia dalam keadaan mengenal Allah, sebagaimana yang ditegaskan dalam firman-Nya, "Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): 'Bukankah Aku ini Tuhanmu?' Mereka menjawab: 'Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi.'" (QS. Al-A'raf: 172).
Relevansi ayat ini dengan Idul Fitri adalah bahwa hari raya tersebut merupakan momentum kembalinya seorang Muslim kepada fitrah, yaitu kondisi suci setelah sebulan penuh menjalani puasa Ramadan. Imam As-Syaukani dalam Fathul Qadir (Jilid 4, 367), menyebutkan bahwa fitrah dalam konteks ini mengacu pada kesucian jiwa setelah dibersihkan melalui ibadah puasa dan ketaatan kepada Allah. Oleh karena itu, setelah Idul Fitri, seorang Muslim diharapkan tetap mempertahankan kesucian dan ketakwaannya dengan terus berpegang teguh pada Islam, sebagaimana yang diperintahkan dalam ayat ini.
Menjaga kefitrian, dalam perspektif tasawwuf dan kesehatan, memiliki keterkaitan yang erat antara keseimbangan fisik, mental, dan spiritual. Dalam perspektif kesehatan, menjaga kefitrian dapat dilakukan dengan pola hidup yang sehat, seperti mengatur pola makan, menjaga keseimbangan antara aktivitas dan istirahat, serta menghindari hal-hal yang dapat merusak tubuh dan jiwa. Ibn Qayyim Al-Jauziyyah dalam At-Tibb An-Nabawi (hal. 18-20) menjelaskan bahwa tubuh memiliki hak yang harus dipenuhi, termasuk dengan mengonsumsi makanan halal dan baik (thayyib), menjaga keseimbangan emosional, serta menghindari kebiasaan yang merusak seperti berlebihan dalam makan dan minum. Dalam teori kesehatan modern, hal ini sejalan dengan konsep holistic well-being, yang menekankan pentingnya keseimbangan nutrisi, aktivitas fisik, dan kesehatan mental agar tubuh tetap dalam kondisi optimal.
Dari perspektif tasawwuf, menjaga kefitrian berarti mempertahankan kemurnian hati dan jiwa dari sifat-sifat tercela serta mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah dan akhlak yang baik. Imam Al-Ghazali dalam Ihya’ Ulumuddin (Jilid 3, 72-74) menjelaskan bahwa hati manusia bagaikan cermin yang dapat berkarat jika terlalu banyak dipenuhi oleh dosa dan kelalaian, dan cara membersihkannya adalah dengan memperbanyak dzikir, muhasabah (introspeksi diri), serta menjauhi sifat riya, sombong, dan dengki. Dalam konteks tasawwuf, kefitrian juga dijaga melalui konsep tazkiyatun nafs (penyucian jiwa), sebagaimana yang dijelaskan dalam Tafsir Ibnu Katsir (Jilid 6, hal. 380) saat menafsirkan QS. Asy-Syams: 9-10, bahwa "Sungguh beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya, dan sungguh merugilah orang yang mengotorinya." Penyucian jiwa ini bisa dilakukan dengan selalu memperbaiki niat, menjauhi maksiat, serta menjalani kehidupan dengan penuh kesederhanaan dan keikhlasan.
Jika tubuh sehat tetapi hati penuh dengan penyakit seperti iri dan dengki, maka kefitrian tidak terjaga secara sempurna. Sebaliknya, jika seseorang hanya berfokus pada ibadah tetapi mengabaikan kesehatan tubuhnya, maka ia tidak bisa optimal dalam menjalankan tugasnya sebagai hamba dan khalifah Allah. Oleh karena itu, Ibnu Ata’illah dalam Al-Hikam (hal. 45-46) mengingatkan bahwa manusia harus menyeimbangkan antara kebutuhan jasmani dan rohani, karena tubuh adalah kendaraan bagi ruh dalam menjalani perjalanan spiritual menuju Allah. Dengan demikian, menjaga kefitrian bukan hanya sekadar kembali kepada kondisi suci setelah Ramadan, tetapi merupakan usaha berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan antara kesehatan fisik, mental, dan spiritual sepanjang hidup.
Dalam kerangka kerja kehidupan yang demikian, seseorang yang mampu menjaga kefitrian memiliki relevansi yang kuat dengan peningkatan kualitas kerja dan kinerja, karena kefitrian mencerminkan kesucian jiwa, keseimbangan mental, dan kesehatan fisik yang berkontribusi langsung terhadap produktivitas dan etos kerja seseorang. Dalam perspektif psikologi, individu yang memiliki kesehatan mental dan spiritual yang baik cenderung lebih fokus, disiplin, dan memiliki tingkat stres yang lebih rendah, sehingga mampu bekerja dengan optimal. Daniel Goleman dalam Emotional Intelligence (1995, 34-35) menjelaskan bahwa kecerdasan emosional yang stabil, termasuk pengendalian diri dan ketenangan jiwa, berpengaruh langsung terhadap efektivitas kerja dan pengambilan keputusan yang lebih bijaksana. Hal ini sesuai dengan konsep kefitrian dalam Islam, yang mengajarkan bahwa manusia harus menjaga hati dan pikiran tetap bersih agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik.
Dari sisi spiritualitas kerja, menjaga kefitrian dapat meningkatkan integritas dan etos kerja, karena seseorang yang senantiasa menjaga kebersihan hati dan jiwanya akan lebih cenderung bekerja dengan penuh tanggung jawab, amanah, dan niat yang lurus. Imam Al-Ghazali dalam Ihya’ Ulumuddin (Jilid 4, 210-212) menyebutkan bahwa pekerjaan yang dilakukan dengan niat yang baik dan hati yang bersih akan menghasilkan keberkahan, sedangkan pekerjaan yang didasarkan pada ambisi duniawi yang tidak sehat akan kehilangan nilai spiritualnya. Kefitrian yang terjaga juga mencerminkan karakter yang jujur, tidak mudah tergoda oleh korupsi, serta mampu membangun hubungan kerja yang harmonis berdasarkan sikap ihsan dan kasih sayang.
Selain itu, dari perspektif kesehatan fisik, kefitrian yang dijaga melalui gaya hidup sehat akan meningkatkan daya tahan tubuh dan energi dalam bekerja. Ibn Qayyim Al-Jauziyyah dalam At-Tibb An-Nabawi (hal. 55-57) menjelaskan bahwa pola makan yang baik, istirahat yang cukup, serta kebersihan fisik akan meningkatkan vitalitas seseorang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, termasuk dalam dunia kerja. Hal ini diperkuat teori work-life balance dalam manajemen modern yang menekankan bahwa keseimbangan antara kesehatan fisik, mental, dan spiritual akan meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja.
Dengan demikian, al-Qur’an begitu jelas memberikan penjelasan proses manusia bisa kembali pada kefitriannya melalui proses puasa selama satu bulan. Islam juga menjelaskan bahwa menjaga kefitrian tidak hanya memiliki manfaat dalam aspek ibadah, tetapi juga memberikan dampak positif dalam dunia profesional. Karyawan atau pemimpin yang menjaga keseimbangan spiritual, emosional, dan fisik akan lebih produktif, memiliki motivasi yang tinggi, serta mampu bekerja dengan penuh dedikasi dan keikhlasan. Oleh karena itu, kefitrian bukan hanya sekadar konsep religius, tetapi juga merupakan fondasi bagi peningkatan kualitas kerja dan kinerja seseorang dalam kehidupan sehari-hari.
Dengan penjelasan yang integrative dan komperehsif seperti inilah, Islam sebaknya diajarkan dalam Pendidikan Islam, terutama di Tingkat Perguruan Tinggi Agama Islam. Islam tidak akan ditemukan kesempuranaan ajarannya jika menggunakan materi yang terpisah (Separated Curriculum), yakni suatu pendekatan dalam sistem pendidikan di mana mata pelajaran atau bidang studi diajarkan secara terpisah tanpa terintegrasi dengan bidang lainnya. Dalam kurikulum ini, setiap mata pelajaran memiliki struktur, tujuan, dan metode pengajaran sendiri tanpa mengaitkannya dengan mata pelajaran lain. UIN Maliki Malang, yang memiliki tagline Kampus Ulul Albab, memiliki arah Pendidikan Islam yang sudah on the right track dengan menjadikan integrasi sebagai visi kelembagaan dan visi akademiknya sekaligus identitas universalnya.
Wallahu A’lam