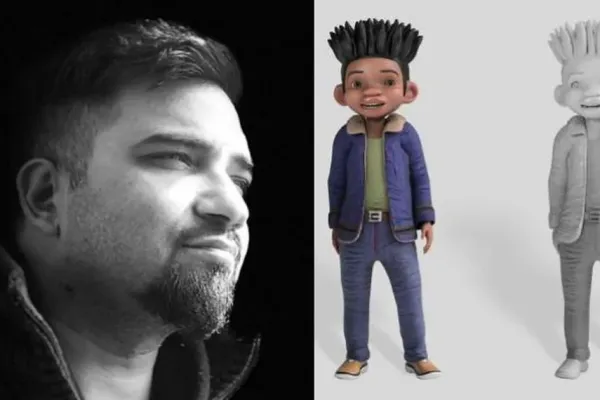Jakarta (ANTARA) - Batangtoru menjadi rumah bagi orangutan tapanuli. Habitat rusak dan menyempit, tersisa 2,5 persen, menyebabkan intensitas konflik antara orangutan tapanuli dan manusia terus meningkat.
Di sisi lain populasi satwa endemik itu merosot. Perlu beragam solusi untuk mengatasi konflik berkepanjangan.
Orangutan tapanuli (Pongo tapanuliensis) merupakan jenis tertua dibanding dengan spesies lain. Indonesia satu-satunya negara di dunia yang memiliki tiga spesies orangutan.
Selain orangutan tapanuli, Indonesia juga memiliki orangutan (Pongo pygmaeus) yang hidup di rimba Kalimantan dan Pongo abelii di hutan Sumatra. Orangutan tapanuli ditetapkan sebagai spesies baru pada November 2017. Namun, kini populasinya terus merosot.
Peneliti orangutan di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Dr. Wanda Kuswanda, M.Sc. memperkirakan populasi orangutan tapanuli kini tersisa 577—760 ekor.
Habitat mereka di Batangtoru, Provinsi Sumatra Utara, seluas 138.435 ha terdiri atas tiga blok. Peneliti dari Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara (USU), Onrizal Ph.D. mengatakan, habitat orangutan tapanuli menyempit, hanya tersisa 2,5 persen dibanding dengan luasan pada 130 tahun lalu.
Keruan saja ketersediaan pakan alami seperti ara (Ficus subulata) dan dadak (Artocarpus lacucha) pun berkurang.
Habitat semakin terfragmentasi akibat konversi hutan untuk lahan budi daya pertanian, perkebunan, dan infrastruktur. Secara umum Pulau Sumatra seluas 47 juta hektare memiliki hutan yang terus menyusut.
Menurut data Belantara Foundation pada 1985 hutan di Pulau Sumatra mencapai 58 persen setara 25,3 juta hektare.
Sepuluh tahun berselang luas hutan tersisa 48 persen. Lalu pada 2016 luas hutan tersisa 24 persen (10,4 juta ha).
Kian menyusutnya habitat orangutan tapanuli itu menyebabkan populasi terisolasi, pakan menurun, reproduksi dan pertumbuhan terganggu, serta terjadi konflik manusia-orangutan tapanuli.
Stigma negatif
Ruang gerak orangutan tapanuli pun makin terbatas. Keruan saja penyempitan hutan itu juga mempersulit daya jelajah orangutan tapanuli.
Menurut Sri Suci Utami Atmoko, Ph.D. dari Forum Konservasi Orangutan Indonesia (Forina) daerah jelajah orangutan sangat luas, mencapai 1.500 hektare bagi orangutan betina dan 5.000 hektare (jantan).
Meski demikian orangutan tapanuli bersifat filopatri, perilaku mahluk hidup dalam mengingat serta kembali ke tempat kelahirannya.
Penjelajah ulung itu sekaligus membawa misi sebagai penyebar aneka biji.
Direktur Belantara Foundation, Dr. Dolly Priatna, menuturkan bahwa orangutan berperan penting untuk keberlanjutan ekosistem. Satwa itu antara lain membantu penyebaran biji di kawasan hutan sehingga mampu membantu regenerasi hutan secara alami dan menjaga keseimbangan ekosistem.
Wanda, Suci, Onrizal, dan Dolly menyampaikan hal tersebut pada seminar nasional orangutan di Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan pada 4 September 2025.
Belantara Foundation adalah organisasi nirlaba independen berdiri pada 2014 yang fokus pada konservasi lingkungan, restorasi hutan, konservasi satwa liar, dan pengembangan masyarakat berkelanjutan di seluruh Indonesia.
Sedianya seminar itu berlangsung pada Agustus untuk memperingati International Orangutan Day setiap 19 Agustus.
Seminar berlangsung secara luring di Gedung Pascasarjana Universitas Pakuan dan daring. Peserta yang mengikuti kegiatan secara daring mencapai 500-an mahasiswa Biologi dari berbagai perguruan tinggi yakni Universitas Riau, Universitas Andalas, Universitas Tanjungpura, Universitas Negeri Jakarta, dan Uiversitas Nusa Bangsa. Mereka membuat program Nonton Bareng.
Pada seminar itu Dolly mengatakan, akibat menyempitnya habitat maka tingkat interaksi antara manusia dan orangutan tapanuli meningkat sehingga menimbulkan konflik. Harap mafhum, sebagian besar populasi orangutan tapanuli hidup di luar kawasan konservasi.
Menurut Dolly konflik manusia dan orangutan tapanuli disebabkan oleh alih fungsi lahan. Doktor Konservasi Biodiversitas Tropika alumnus Institut Pertanian Bogor itu juga mengatakan, meluasnya pembangunan yang tidak berkelanjutan pada habitat orangutan tapanuli turut memicu konflik.
“Konflik manusia-satwa liar didorong oleh peningkatan populasi manusia, pembangunan infrastruktur, dan aktivitas ekonomi berbasis lahan,” kata Dolly yang juga dosen di Program Studi Manajemen Lingkungan Universitas Pakuan.
Akibat konflik itu kerugian ekonomi bagi masyarakat lokal, termasuk kerusakan tanaman, ternak, dan rumah, serta dapat menyebabkan kematian bagi manusia dan satwa liar.
Dolly mengatakan, secara umum konflik (human-wild life conflict, HWC) menyebabkan beberapa hal seperti perusakan terhadap komoditas pertanian, pengurangan ternak, dan produksi komoditas dan bisnis.
Konflik itu juga menyebabkan serangan terhadap manusia, penularan penyakit ke ternak atau manusia, kehilangan properti, pembangunan berkelanjutan, dan dinamika sosial.
Ibarat pepatah menang jadi arang, kalah jadi abu, melukiskan kehancuran total akibat konflik antara manusia dan orangutan tapanuli di habitat alaminya. Bagi orangutan, konflik itu mengakibatkan stres bahkan kematian.
Di pihak lain petani pun mengalami gagal panen. Jadi, dalam konflik itu baik pihak yang menang maupun yang kalah akan sama-sama menderita kerugian.
Celakanya konflik itu juga menumbuhkan persepsi negatif terhadap satwa liar antara lain stigma sebagai hama.
Dosen di Departemen Antropologi Universitas Indonesia, Sundjaya, mengatakan bahwa respons terhadap orangutan adalah bagian dari praktik pengendalian hama.
Sundjaya mengutip hasil riset Yapeka-Unesco (2010) yang menyebutkan bahwa 68,3 persen petani menganggap orangutan sebagai hama.
Riset lain oleh Valerie Marchal dan Catherine Hill (2009) menunjukkan 51,2 persen petani menganggap orangutan sebagai hama. Yapeka menempatkan babi hutan (Sus sacrofa) sebagai hama nomor satu dan orangutan nomor empat.
Sementara itu riset Marchal dan Hill menempatkan kera ekor panjang (Macaca fascicularis) sebagai hama nomor satu dan orangutan tapanuli sebagai hama nomor empat.
Di Tapanuli Selatan acapkali orangutan “memanen” durian (Durio zibethinus), petai (Parkia speciosa), jengkol (Pithecellobium jiringa), dan mangga (Mangifera indica) milik warga.
Bukan hanya itu, orangutan juga makan beragam komoditas seperti umbut sawit, kambium akasia, eukaliptus, dan karet.
Sejatinya pengambilan buah itu sebagai konsekuensi logis akibat menyempitnya habitat orangutan tapanuli.
“Orangutan memasuki kebun masyarakat dan memakan buah-buahan ketika musim buah karena tidak ada lagi makanan,” kata Edy Hendras Wahyono dari Orangutan Foundation International.
Satwa frugivor alias pemakan buah itu harus bertahan hidup sehingga mencari pakan di habitat yang kini berubah menjadi perkebunan warga. Oleh karena itu, konflik antara manusia dan orangutan tapanuli tak terelakkan.
Solusi konflik
Menurut Onrizal orangutan tapanuli kian sering muncul di kebun warga. Oleh karena itu, pada musim buah durian, petai, dan jengkol, interaksi orangutan-manusia cenderung meningkat. Pada umumnya masyarakat mengatasinya dengan pengusiran.
“Mitigasi berbasis ekologi sangat minim,” ujar Onrizal. Menurut doktor Biologi alumnus Universiti Sains Malaysia itu untuk mengatasi konflik manusia-orangutan antara lain dengan restorasi dengan menanam pohon yang merupakan pakan khas.
Sekadar menyebut beberapa contoh adalah temayang (Xerospermum noronhianum) yang berbuah sepanjang tahun atau bendo (Artocarpus elasticus).
“Ketersediaan pakan alami mengurangi ketergantungan pada kebun,” kata Onrizal. Hal serupa disampaikan oleh Wanda.
Peneliti ahli utama BRIN itu mengatakan, mitigasi berbasis ekologi dengan perlindungan dan pemulihan ekosistem atau lanskap ditempuh dengan restorasi habitat kawasan hutan, pengembangan koridor sebagai area preservasi, dan minimalisasi degradasi dan isolasi pada lahan hak guna usaha.
Menurut Wanda pengembangan ekonomi alternatif juga penting untuk mencegah konflik. Ekonomi alternatif itu berupa desa ekowisata, perikanan, dan usaha jasa, skema insentif konservasi berupa kompensasi nontunai, skema karbon, serta perhutanan sosial.
Menurut Wanda perlu peningkatan kapasitas pengelola dan masyarakat dengan penyuluhan dan kampanye untuk mengubah persepsi orangutan dari hama menjadi petani hutan.
Cara lain berupa pelatihan, pendidikan konservasi, dan pengelolaan lahan berkelanjutan, serta peningkatan riset dan diseminasi di daerah.
Revitalisasi kearifan lokal dan budaya dalam pengelolaan hutan dan lahan sebuah keniscayaan untuk mencegah konflik berkepanjangan.
Revitalisasi itu sebaiknya juga melibatkan generasi muda. Selain itu, menurut Wanda, perlu penguatan kebijakan seperti Peraturan Presiden) dan kolaborasi para pihak antara lain akademisi, pemerintah, masyaratat, dan media massa.
Sejatinya Keputusan Gubernur Sumatra Utara No. 188.44/156/KPTS/2025 mengatur perlindungan dan pengelolaan terpadu ekosistem Batangtoru.
Keputusan itu menekankan pendekatan strategis melalui penguatan tata kelola dengan pembentukan rencana perlindungan dan pengelolaan kelembagaan dan pembiayaan berkelanjutan.
Selain itu keputusan itu juga menekankan kolaborasi dan komunikasi multipihak seperti pemerintah, swasta, masyarakat, akademisi, dan media massa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengelolaan ekosistem.
Kebijakan itu juga melibatkan masyarakat dengan mendorong mereka sebagai aktor utama pengembangan ekonomi lokal berbasis hutan dan agroforestri.
Menurut Onrizal pengembangan agroforestri ramah satwa sebagai zona penyangga sekaligus koridor ekologis untuk konektivitas.
Bahkan keputusan itu juga mengatur integrasi dan pengelolaan ekosistem Batangtoru dalam kebijakan tata ruang dan rencana pembangunan daerah.
Pendekatan koeksistensi
Pendekatan lain utnuk mengatasi konflik orangutan tapanuli dan manusia adalah C2C, singkatan dari conflict to coexistense (dari konflik menjadi koesistensi).
Pada prinsipnya koeksistensi adalah keadaan hidup berdampingan dua pihak atau lebih yang berbeda atau bertentangan.
Koeksistensi biologi adalah mengelola spesies dalam suatu komunitas pada suatu ruang dan waktu yang sama (Davin dan Murray, 2019).
Singkat kata, koeksistensi dalam konteks ini adalah masyarakat di sekitar Batangtoru hidup berdampingan dan hormonis dengan orangutan tapanuli.
C2C dikembangkan oleh World Wide Fund for Nature (WWF) dan para ahli konflik manusia-satwa liar, termasuk orangutan.
Menurut Alexandra Zimmermann koesistensi merupakan pendekatan holistik dan adaptif yang memerlukan pembelajaran dan dialog berkelanjutan. Tujuannya bukan menyelesaikan semua konflik.
Sebab, konflik akan selalu ada dan merupakan bagian dari kehidupan. Sebaliknya, tujuannya mengelola konflik dan menghasilkan kondisi agar hidup berdampingan, berkembang, dan menjadi bagian kehidupan.
Menurut Dolly pendekatan C2C harus mendefinisikan empat hasil utama yakni satwa liar, hidup berdampingan, habitat, dan mengamankan mata pencaharian/aset.
Prinsip utama dalam pendekatan koesistensi adalah menjaga toleransi, berbagi tanggung jawab, membangun ketahanan, dan mengedepankan holisme (holistik, menyeluruh).
Dolly mengatakan, kondisi kunci agar koeksistensi dapat terwujud dengan memperhatikan pelestarian dan pemulihan habitat, perencanaan penggunaan lahan berkelanjutan, keterlibatan komunitas dan pendidikan manajemen konflik manusia-satwa liar, penghidupan berkelanjutan, kerangka hukum dan penegakannya.
Selain itu kondisi lain yang diperlukan untukmewujudkan koeksistensi adalah penelitian ilmiah dan pemantauan, kolaborasi dan kemitraan, kerja sama internasional, kebijakan yang mendukung, komitmen jangka panjang, kesadaran dan advokasi masyarakat, serta pertimbangan budaya dan etis.
“Koeksistensi dapat terwujud apabila manusia menyetarakan pemenuhan kepentingan ekonomi, sosial, dan budaya dengan kepentingan ekologis bagi orangutan,” kata Wanda.
Pendekatan koeksisensi juga mengharuskan masyarakat dan pengelola lahan memahami bahwa mereka berbagi ruang atau menempati ruang yang sama dengan orangutan tapanuli. Selain itu perlu pengembangkan manfaat ekonomi dari keberadaan satwa liar untuk mendorong koeksistensi.
Pemerintah pusat dan daerah harus memprioritaskan konservasi satwa liar dalam perencanaan tata ruang dan pembangunan infrastruktur, serta menegakkan hukum secara tegas terhadap kejahatan kehutanan dan satwa liar.
“Pendekatan terpadu ini dapat mengarah pada pembangunan berkelanjutan dengan menyeimbangkan kepentingan ekonomi, infrastruktur, sosial, dan lingkungan,” kata Dolly.
Menurut Onrizal koeksistensi dapat diwujudkan dengan syarat pakan orangutan cukup sehingga mereka tetap di hutan, pemberdayaan masyarakat, dan kebijakan tata ruang yang menekankan pada perlindungan habitat.
“Pakan itu jembatan menuju koeksistensi. Saat pakan tersedia, konflik mereda. Saat hutan terjaga, koeksistensi tercipta,” kata Onrizal.
*) Penulis adalah Dosen Komunikasi Pertanian dan Lingkungan Universitas Pakuan.