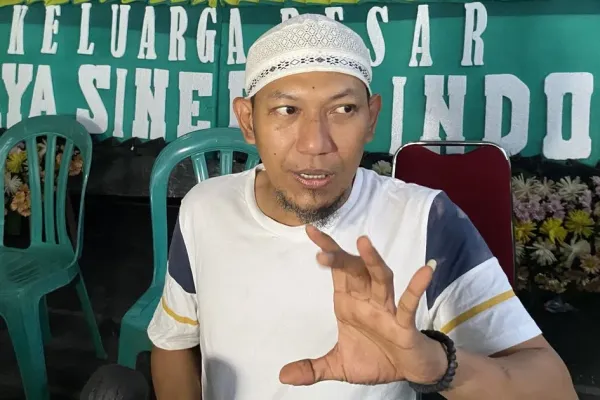Ketika generasi muda terbiasa mengonsumsi dan bangga pada produk lokal, maka pasar untuk petani kecil, UMKM, dan komunitas adat akan tumbuh
Jakarta (ANTARA) - Generasi muda hari ini tumbuh di tengah derasnya arus globalisasi yang menawarkan berbagai pilihan gaya hidup, makanan, dan budaya.
Namun, justru di tengah keterbukaan tersebut, ada peluang besar untuk memperkuat kembali akar identitas bangsa melalui pangan lokal dan budaya nusantara. Bukan hanya soal makan, tetapi bagaimana pangan tradisional dapat dibudayakan menjadi bagian dari keseharian Gen Z.
Inilah yang sebetulnya sedang diupayakan lewat berbagai gerakan masyarakat, salah satunya melalui ajang seperti Festival Panen Raya Nusantara (PARARA) 2025 yang digelar di Jakarta beberapa waktu lalu.
Meski hanya dua hari, festival ini menjadi contoh bagaimana ruang pertemuan antara pangan lokal, tradisi nusantara, dan generasi muda bisa tercipta.
Sejak 2015, PARARA konsisten menjadi wadah bagi komunitas adat, produsen pangan sehat, hingga pengrajin dari seluruh nusantara untuk memperkenalkan produk mereka.
Pada 2025, lebih dari 16 komunitas ikut terlibat, membawa pangan lokal, kerajinan, hingga fesyen berbasis kain tradisional.
Hal terpenting dari event tersebut bukanlah keramaian acaranya, melainkan pesan mendalam bahwa pangan nusantara bukan sekadar komoditas yang dikonsumsi sesekali, tapi juga warisan budaya yang harus terus dirawat agar menjadi tradisi hidup generasi muda.
Format yang kini lebih kekinian memang sengaja dihadirkan agar Gen Z merasa dekat, tidak canggung, dan akhirnya tertarik menjadikan pangan dan budaya lokal bagian dari gaya hidupnya.
Menariknya, pertemuan lintas generasi di ajang ini terlihat jelas. Salah satunya melalui karya desainer muda dari LaSalle School Jakarta yang menghadirkan koleksi pakaian bertema Hybrid.
Meski berbicara soal fesyen, pesan yang lahir tetap sama yakni bagaimana warisan nusantara dapat hadir dalam keseharian anak muda tanpa kehilangan sisi modernitasnya.
Tenun Biboki asal Nusa Tenggara Timur, misalnya, dipadukan dengan bahan modern seperti organza, lame, atau taffeta, membentuk identitas baru yang tak terputus dari tradisi.
Kisah serupa juga hadir dari Papua, lewat tangan seorang pengrajin noken bernama Teresia Kopon. Di sela festival, ia mengajarkan cara menggulung benang kulit kayu kepada anak-anak muda.
Aktivitas sederhana itu menjadi simbol bahwa tradisi yang dulu mungkin hanya dianggap milik masyarakat adat, kini bisa dipelajari dan dihidupi kembali oleh generasi perkotaan.
Teresia mengaku senang melihat semangat anak muda yang meskipun kesulitan menggulung benang, mereka tetap berusaha dan tertawa bersama.
Itulah potret pentingnya proses pewarisan tradisi, bukan hanya lewat konsumsi produk jadi, tapi juga lewat pengalaman membuat, belajar, dan merasakan langsung nilai di balik sebuah karya.
Investasi Keberlanjutan
Jika dalam dunia fesyen dan kerajinan tangan seperti token, Gen Z bisa membangun jembatan antara modernitas dan tradisi, mengapa tidak dalam dunia pangan?
Dukungan terhadap upaya pelestarian pangan lokal datang dari pemerintah. Dr. Julianus Limbeng, Pamong Budaya Ahli Madya dari Kementerian Kebudayaan, menegaskan pentingnya menghadirkan pangan lokal nusantara ke ruang publik.
Menurut dia, gerakan ini memberi kontribusi nyata dalam memperkenalkan kekayaan pangan Indonesia. Apresiasi dari pemerintah menjadi pengingat bahwa membangun budaya pangan lokal bukan sekadar romantisme masa lalu, melainkan investasi kebudayaan dan keberlanjutan.
Sistem pangan yang adil, sehat, dan berkelanjutan hanya bisa tercapai jika generasi muda menganggapnya relevan dengan hidup mereka, bukan sebagai sesuatu yang asing atau kuno.
Gen Z memang memiliki karakteristik unik, kritis, digital native, dan sangat peduli pada isu lingkungan maupun keadilan sosial. Mereka cenderung memilih produk yang bukan hanya enak, tetapi juga punya cerita, nilai, dan dampak.
Di sinilah pangan dan budaya lokal nusantara bisa masuk sebagai jawaban. Beras organik dari komunitas adat, kopi dari hutan lindung, atau sagu dari tanah Papua yang tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga membawa kisah tentang keberlanjutan, pemberdayaan, dan identitas bangsa.
Jika cerita-cerita itu bisa dikemas dan disampaikan dengan cara yang relevan bagi Gen Z, maka konsumsi pangan lokal akan berkembang menjadi tradisi baru yang mengakar.
Membudayakan pangan nusantara bukan berarti menolak makanan global, melainkan menciptakan keseimbangan. Sama seperti hybrid fashion yang memadukan kain tradisional dengan potongan modern, pangan lokal pun bisa hadir dalam bentuk baru yang sesuai selera anak muda.
Nasi jagung bisa dipadukan dengan lauk kekinian, singkong bisa hadir dalam bentuk dessert modern, atau jamu bisa dikemas dalam botol praktis dengan desain yang instagramable. Kreativitas inilah yang akan membuat pangan nusantara bukan sekadar romantisme masa lalu, tetapi gaya hidup masa depan.
Lebih jauh, pembudayaan pangan nusantara untuk Gen Z juga berarti membangun kedaulatan pangan bangsa. Ketika generasi muda terbiasa mengonsumsi dan bangga pada produk lokal, maka pasar untuk petani kecil, UMKM, dan komunitas adat akan tumbuh.
Ini akan memperkuat ekonomi lokal sekaligus menjaga ekosistem sosial budaya. Bayangkan jika setiap anak muda di Jakarta, Bandung, atau Surabaya terbiasa memilih pangan lokal setiap kali belanja. Dampaknya bukan hanya pada dompet petani, tapi juga pada kelestarian hutan, air, dan tanah kita.
Oleh karena itu, penting sekali menghadirkan ruang-ruang perjumpaan, tempat pangan lokal tidak hanya diperkenalkan, tapi juga dialami, diceritakan, dan dibudayakan.
Ajang seperti festival hanyalah pintu masuk. Hal yang lebih penting adalah bagaimana tradisi ini bisa terus hidup di rumah, di sekolah, di kafe, dan di ruang digital yang setiap hari diakses Gen Z.
Jika generasi muda sudah terbiasa melihat, merasakan, dan membicarakan pangan lokal sebagai bagian dari identitas mereka, maka tradisi nusantara tidak akan pernah punah.
Pada akhirnya, menghadirkan pangan lokal sebagai tradisi bagi Gen Z adalah tentang memberi mereka alasan untuk merasa bangga sekaligus relevan.
Pangan lokal bukan sekadar soal apa yang kita makan, tetapi bagaimana kita memaknai kehidupan, keberlanjutan, dan kebersamaan. Generasi muda adalah jembatan antara masa lalu dan masa depan.
Jika mereka mampu menjadikan pangan nusantara bagian dari keseharian, maka kita tidak hanya menjaga warisan, tetapi juga memastikan tradisi itu tumbuh, berkembang, dan tetap hidup untuk generasi berikutnya.
Itulah esensi membudayakan pangan nusantara, sebuah warisan yang terus menyatu dalam denyut kehidupan bangsa.
*) Penulis adalah Ketua Steering Committee PARARA.