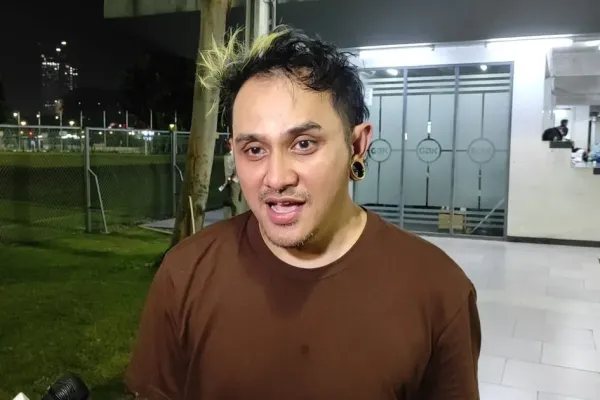Reformasi Polri sejatinya adalah tanggung jawab bersama antara negara, aparat, dan masyarakat sipil
Jakarta (ANTARA) - Rentetan peristiwa dalam beberapa pekan terakhir, mulai dari demonstrasi besar di berbagai kota hingga insiden pengemudi ojek online, kembali memicu sorotan tajam terhadap institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Di tengah situasi tersebut, muncul desakan dari sebagian pihak agar Kapolri segera diganti. Namun, benarkah pergantian pimpinan puncak adalah solusi?
Di satu sisi, tuntutan publik atas akuntabilitas memang wajar. Kepolisian adalah institusi negara yang langsung bersentuhan dengan warga.
Namun di sisi lain, mengandalkan pergantian Kapolri sebagai jawaban atas kompleksitas persoalan institusional justru dapat menyesatkan arah reformasi. Sebab, persoalan utama bukan sekadar pada figur, melainkan menyangkut reformasi struktural, reformasi instrumental dan reformasi kultural.
Reformasi Polri digaungkan sebelum diterbitkannya UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Keseriusan itu juga diwujudkan dalam kebijakan berbentuk peta jalan reformasi kepolisian "Grand Strategy Polri". Tahun 2025 merupakan momentum strategis dalam perjalanan reformasi Polri.
Saat ini, institusi Polri sedang mempersiapkan Grand Strategy Polri 2025–2045, kelanjutan dari strategi sebelumnya yang berlaku pada periode 2005–2025. Dalam dokumen ini, reformasi tidak hanya dimulai dari gagasan, tetapi juga adaptasi dengan perkembangan teknologi, kompleksitas kejahatan, hingga tuntutan transparansi publik.
Visi "Polri Presisi" (prediktif, responsif, transparan, dan berkeadilan) yang digaungkan oleh Kapolri Listyo Sigit Prabowo sejak 2021, pelan tapi pasti, sedang diupayakan untuk menyatu dalam sistem dan budaya kerja Polri.
Polri Presisi menyasar transformasi Polri secara menyeluruh. Tak hanya sisi operasional, tetapi juga penguatan sistem pengawasan internal, tata kelola sumber daya manusia, dan pelayanan publik berbasis teknologi.
Reformasi Polri, melalui Polri Presisi telah menekankan juga pada aspek moral dan etik. Profesionalisme aparat kepolisian tidak hanya diukur dari kemampuan teknis, melainkan dari integritas dan kemampuannya bersikap humanis terhadap masyarakat.
Pendidikan dan pelatihan di tubuh Polri perlu ditekankan pada penguatan karakter, empati sosial, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Maka, langkah Kapolri untuk merespons cepat terhadap tragedi ojol pada demonstrasi besar-besaran di Jakarta beberapa waktu yang lalu haruslah dilihat dari kacamata upaya untuk perbaikan dan memberikan teladan dalam membangun empati sosial. Pada kenyataannya langkah untuk membangun empati ini juga didukung oleh sejumlah pejabat dan institusi lainnya.
Reformasi proporsional
Penting dicatat, tuntutan masyarakat bukan menolak institusi, tetapi menagih janji reformasi. Insiden seperti tewasnya warga sipil dalam penanganan demonstrasi bukan hanya menjadi tragedi kemanusiaan, tetapi juga ada faktor psikologi massa yang harus dihadapi oleh petugas lapangan sehingga menimbulkan dilema dalam mengambil keputusan secara cepat saat itu.
Dalam kondisi seperti ini, wacana mengganti Kapolri memang menggema. Namun, langkah tersebut harus ditempatkan secara proporsional. Kapolri sejak 2021 telah mengawal implementasi Polri Presisi sesuai dengan agenda reformasi Polri dalam Grand Strategy.
Dalam konteks ini, sistem kerja Polri telah mengalami perubahan fundamental. Tapi memang, terkait kultur tidak bisa diubah dalam waktu singkat. Perubahan kultur organisasi membutuhkan keteladanan dalam waktu yang tidak pendek dibanding aspek struktural dan instrumental.
Reformasi kultural Polri adalah aspek paling krusial, mencakup perubahan mindset, nilai, dan budaya kerja dari feodal-patrimonial menjadi profesional dan humanis. Ini menuntut keteladanan pimpinan, bukan sekadar instruksi atau pencitraan.
Tanpa transformasi budaya institusional, reformasi struktural hanya kosmetik. Reformasi sejati lahir dari kesadaran, tanggung jawab, dan integritas di semua lini.
Sebaliknya, sikap sejumlah organisasi masyarakat seperti Nahdlatul Ulama, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Muhammadiyah yang mengimbau agar tidak tergesa-gesa mengganti Kapolri dinilai lebih objektif.
Menjaga stabilitas dalam institusi Polri itu sendiri lebih diutamakan, mengingat Polri adalah pilar penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban nasional. Instabilitas di dalam tubuh Polri dapat mengganggu agenda pengamanan secara nasional dan ini merugikan.
Reformasi yang sejati tidak bisa dibangun di atas tekanan sesaat, melainkan proses yang terukur. Oleh karena itu, alih-alih menjadikan pergantian Kapolri sebagai jawaban utama, fokus reformasi semestinya diarahkan pada langkah-langkah strategis.
Reformasi Polri menekankan pentingnya perubahan kultural, bukan sekadar pencopotan Kapolri. Perubahan mindset, nilai, dan budaya birokrasi jadi hal paling mendesak untuk menciptakan institusi yang profesional, humanis, dan akuntabel. Tanpa reformasi kultural dan kepemimpinan transformatif, pergantian pimpinan hanya bersifat simbolik dan tak menyentuh akar persoalan institusional.
Dalam konteks transformasi Polri Presisi terdapat empat pilar utama transformasi, berupa transformasi organisasi, transformasi pelayanan publik, transformasi operasional dan transformasi pengawasan. Sesuai konteks yang berkembang, penulis menambahkan lima langkah strategis.
Pertama, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem komando dan pelibatan kekuatan dalam pengamanan unjuk rasa. Pendekatan berbasis dialog dan deeskalasi konflik harus diutamakan. Evaluasi dapat berfokus pada sejumlah hal penting seperti sistem komando, pelibatan kekuatan, penyediaan negosiator, pemetaan aktor lapangan, dan revisi SOP penanganan unjuk rasa masyarakat.
Kedua, memperkuat komunikasi publik. Kepolisian harus tampil terbuka, tidak defensif, dan mampu menjelaskan kebijakan serta tindakan secara jernih kepada masyarakat. Mematuhi implementasi UU nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik secara otomatis akan memperkuat transparansi secara menyeluruh. Komunikasi publik berperan untuk mempertajam hal-hal yang diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Ketiga, membangun sistem pengawasan yang independen dan transparan memerlukan pelibatan aktif lembaga eksternal seperti Komnas HAM, Ombudsman, dan masyarakat sipil. Mereka harus diberi akses terhadap informasi, ruang partisipasi dalam investigasi, serta wewenang memberi rekomendasi. Keterbukaan ini akan memperkuat akuntabilitas Polri dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas serta profesionalisme institusi kepolisian.
Keempat, memperkuat pelatihan dan pendidikan kepolisian berbasis etik, empati, dan hak asasi manusia sangat penting untuk membentuk karakter humanis. Kurikulum harus menyentuh aspek moralitas secara mendalam, tidak hanya keterampilan teknis. Pendidikan ini akan menanamkan nilai integritas, kepekaan sosial, serta komitmen terhadap keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.
Kelima, mempercepat digitalisasi pelayanan publik dan sistem pelaporan penting untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan responsifitas Polri. Masyarakat harus diberi akses yang mudah, cepat, dan aman dalam melaporkan pelanggaran, meminta perlindungan hukum, atau memantau proses penanganan kasus. Inovasi digital ini akan memperkuat kepercayaan publik serta mendorong keterlibatan aktif warga dalam penegakan hukum.
Kapolri saat ini tentu memiliki tanggung jawab besar untuk menjawab tantangan ini. Namun, publik juga perlu memahami bahwa perubahan institusional tidak bisa digantungkan pada satu orang. Diperlukan sinergi antara pimpinan, jajaran internal Polri, masyarakat, dan pemerintah agar reformasi berjalan sesuai arah yang diharapkan.
Apa yang dicapai Polri menemukan padanannya di tingkat global. Prof. Mahfud MD menyamakan Polri dengan Scotland Yard, kepolisian metropolitan London. Keduanya unggul dalam investigasi, profesionalisme, teknologi, serta mendorong reformasi, digitalisasi layanan, kerja sama internasional, dan pendekatan humanis dalam menjaga keamanan secara demokratis dan beretika.
Dalam demokrasi yang sehat, kritik terhadap institusi adalah bentuk kepedulian. Namun kritik yang konstruktif adalah yang mendorong perbaikan sistem, bukan yang berhenti pada kecaman personal. Reformasi Polri sejatinya adalah tanggung jawab bersama antara negara, aparat, dan masyarakat sipil.
Dengan arah kebijakan yang jelas, komitmen moral yang kuat, dan pengawasan publik yang aktif, institusi kepolisian Indonesia dapat berbenah menuju profesionalisme yang sejati: menjaga hukum, melindungi masyarakat, dan menegakkan keadilan dengan humanis.
Pada akhirnya, pendayagunaan segala kekuatan keamanan nasional disinergikan dengan semua komponen bangsa adalah kunci untuk menjaga stabilitas keamanan guna mencapai tujuan menjadi bangsa yang kuat dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.
*) Ngasiman Djoyonegoro adalah Analis Intelijen, Pertahanan dan Keamanan