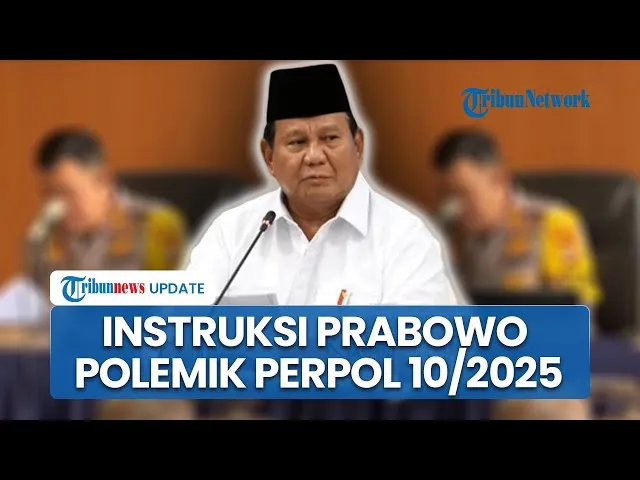Jakarta (ANTARA) - Hari Ibu hampir selalu hadir dalam wajah yang sama. Ucapan terima kasih mengalir, pengorbanan ibu dipuja, ketabahannya diangkat sebagai standar kebajikan.
Ibu digambarkan sebagai sosok yang nyaris tanpa cela, selalu kuat, selalu sabar, selalu benar. Dalam narasi ini, keibuan menjadi simbol yang rapi dan menghangatkan.
Narasi tersebut tentu lahir dari niat baik. Ia menjadi cara kolektif untuk menghormati peran yang sering luput dari pengakuan formal.
Di banyak keluarga, ibu memang memikul beban ganda: mengasuh, mengelola rumah, menopang emosi keluarga, bahkan ikut menjaga stabilitas ekonomi. Perayaan Hari Ibu memberi ruang bagi rasa terima kasih yang kerap tertunda.
Namun, di situlah persoalannya. Ketika satu narasi diputar berulang, ia perlahan menjadi satu-satunya cerita yang dianggap sah.
Ibu tidak lagi diposisikan sebagai manusia dengan pengalaman beragam, melainkan sebagai figur ideal yang harus selalu dipuja. Segala yang tidak selaras dengan gambaran itu cenderung disisihkan, dianggap tidak pantas hadir di hari perayaan.
Dalam ruang publik, hampir tidak ada tempat bagi pembicaraan tentang ibu yang lelah, keliru, atau terjebak dalam cara-cara pengasuhan yang problematis.
Keibuan diperlakukan sebagai wilayah sakral yang tak boleh disentuh kritik, seolah mempertanyakan praktiknya sama dengan meniadakan jasa dan cinta itu sendiri.
Akibatnya, Hari Ibu kerap menjadi perayaan peran, bukan refleksi relasi. Yang dirayakan adalah fungsi sosial ibu, bukan dinamika nyata hubungan ibu dan anak yang sering kali kompleks.
Padahal relasi keluarga, seperti relasi manusia pada umumnya, tidak selalu berjalan mulus dan ideal.
Narasi yang terlalu tunggal ini tidak sepenuhnya salah, tetapi jelas tidak lengkap. Ia menenangkan, namun juga menyederhanakan.
Ia memuliakan, namun sekaligus membungkam sisi-sisi yang tidak sesuai dengan gambaran ideal.
Mungkin di sinilah Hari Ibu perlu diberi makna yang lebih luas. Bukan untuk mengurangi penghormatan, melainkan untuk memperkaya pemahaman.
Sebab penghargaan yang matang tidak hanya lahir dari pujian, tetapi juga dari keberanian melihat kenyataan apa adanya, dengan jujur dan berimbang.
Ada (juga) luka
Di balik narasi perayaan yang rapi, relasi ibu dan anak dalam kehidupan nyata sering kali jauh lebih rumit. Tidak semua hubungan dibangun di atas kehangatan dan rasa aman.
Dalam sejumlah kasus, relasi tersebut justru diwarnai ketegangan yang berlangsung lama dan kerap tak terucapkan.
Salah satu pola yang muncul adalah penggunaan relasi kuasa dalam pengasuhan, bahkan ketika anak telah memasuki usia dewasa.
Atas nama pengalaman, pengorbanan, atau kasih sayang, sebagian ibu tetap merasa berhak mengatur pilihan hidup anak, dari urusan karier hingga relasi personal.
Kontrol ini sering tidak dikenali sebagai masalah, karena dibungkus dalam bahasa kepedulian.
Dalam konteks masyarakat religius, tekanan tersebut kadang diperkuat oleh istilah moral dan spiritual.
Ancaman “durhaka” menjadi batas yang membuat anak sulit bersuara. Kepatuhan lahir bukan dari kedekatan emosional, melainkan dari rasa takut melanggar norma dan nilai yang dianggap sakral.
Hubungan pun berjalan timpang: hormat terjaga, tetapi keintiman menghilang.
John Bowlby dan Mary Ainsworth, dua psikolog yang mengembangkan Teori Kelekatan mengungkapkan bahwa relasi yang dibangun di atas rasa takut dan kontrol cenderung melahirkan kepatuhan semu, bukan kelekatan emosional yang sehat.
Dominasi juga tidak selalu memerlukan kuasa nyata. Dalam banyak relasi, kendali dipertahankan melalui emosi: mudah tersinggung, menyimpan marah, atau memosisikan diri sebagai pihak yang selalu terluka.
Perbedaan pendapat dibaca sebagai pembangkangan, sementara dialog kerap berhenti, sebelum benar-benar dimulai.
Kesenjangan pengalaman antargenerasi turut memperumit situasi. Banyak ibu dibesarkan dalam lingkungan dengan pilihan hidup terbatas dan minim ruang dialog emosional.
Ketahanan lebih dihargai daripada keterbukaan perasaan. Pola ini kemudian terbawa ke praktik pengasuhan, tanpa selalu disadari dampaknya bagi anak.
Penting dicatat, kekerasan dalam relasi keluarga tidak selalu berwujud fisik atau verbal yang kasar. Ia bisa hadir dalam bentuk simbolik dan emosional, rapi, berulang, dan sulit dikenali.
Tak sedikit anak baru memahami bahwa relasinya tidak sehat setelah dewasa, ketika bahasa untuk mengenali luka akhirnya tersedia.
Mengakui kenyataan ini bukan berarti meniadakan cinta dan pengorbanan ibu. Namun memahami konteks juga tidak serta-merta menghapus dampak.
Relasi yang melukai tetap meninggalkan jejak, meskipun lahir dari niat yang dianggap baik.
Memutus siklus
Di titik inilah Hari Ibu dapat diberi makna yang lebih luas. Bukan semata sebagai perayaan peran, melainkan sebagai ruang refleksi bersama tentang relasi dan tanggung jawab lintas generasi.
Penghormatan terhadap ibu tidak harus berhenti pada puja-puji, tetapi dapat berkembang menjadi upaya sadar untuk membangun hubungan yang lebih sehat.
Mengakui bahwa sebagian relasi ibu dan anak menyisakan luka bukanlah bentuk pembangkangan moral.
Sebaliknya, pengakuan tersebut menjadi langkah awal untuk memahami bahwa cinta tidak selalu hadir dalam praktik yang tepat.
Niat baik tidak selalu menghasilkan dampak yang baik, terutama ketika kuasa, ketakutan, dan komunikasi yang timpang dibiarkan berlangsung tanpa koreksi.
Bagi generasi yang hari ini menjadi orang tua, atau sedang menuju ke sana, refleksi ini menjadi penting.
Pertanyaannya bukan lagi siapa ibu yang paling berkorban, melainkan bagaimana keibuan dijalankan dalam keseharian.
Apakah anak diberi ruang untuk bertumbuh sebagai individu yang utuh, atau justru dipelihara dalam kepatuhan yang sunyi.
Pendekatan pengasuhan reflektif menekankan pentingnya kesadaran diri orang tua terhadap luka dan pola relasinya sendiri, agar tidak diwariskan secara otomatis kepada anak.
Memutus siklus tidak berarti memutus hubungan. Ia berarti mengganti cara. Mengganti ancaman dengan dialog, kontrol dengan kepercayaan, serta tuntutan moral dengan kehadiran emosional.
Ia juga berarti berani menyadari bahwa kehilangan kendali bukan kehilangan cinta. Anak yang dewasa tidak sedang meninggalkan orang tuanya, melainkan sedang menjalani hidupnya sendiri.
Hari Ibu dapat menjadi momentum untuk menggeser cara pandang tersebut. Bukan hari untuk menutup mata dari kenyataan yang tidak nyaman, melainkan kesempatan untuk memperluas pemahaman tentang kasih yang lebih adil.
Kasih yang tidak menuntut, tidak melukai, dan tidak menjadikan pengorbanan sebagai alat kendali.
Generasi yang sadar akan lukanya memiliki tanggung jawab etis untuk tidak mewariskannya. Kesadaran ini tidak selalu mudah, karena ia menuntut keberanian untuk belajar, mengoreksi diri, dan pada saat tertentu, meminta maaf.
Namun di situlah letak keibuan yang bijaksana dalam praktik, bukan sekadar dalam citra.
Dengan cara itu, Hari Ibu tidak lagi berhenti sebagai perayaan simbolik. Ia menjadi penanda proses panjang menuju relasi yang lebih sehat, setara, dan manusiawi.
Sebab menghormati ibu pada akhirnya bukan hanya tentang mengenang masa lalu, tetapi tentang memastikan masa depan yang lebih baik bagi generasi berikutnya.