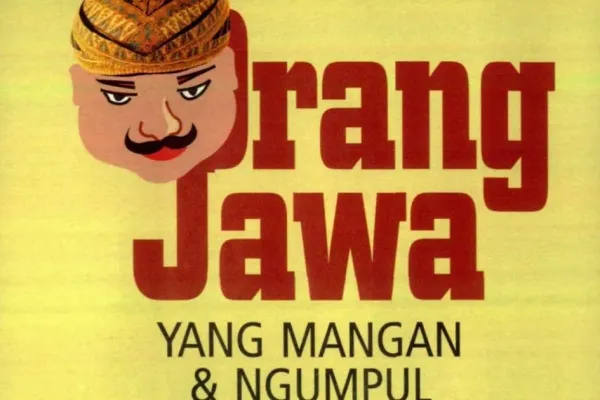
Keturunan suku Jawa dikenal sebagai salah satu pendatang yang membentuk sebuah komunitas besar di Tanjungpinang, di samping komunitas Cina, komunitas Bugis, serta orang-orang Melayu sendiri – pada 2010 angkanya mencapai 27,9 persen. Diduga mereka datang dalam beberapa gelombang, seiring perubahan situasi politik di Nusantara, mulai zaman Belanda, Jepang, hingga Kemerdekaan.
Ditulis oleh Arif Wijaya di Jakarta, tayang pada Agustus 2010
---
Intisari hadir di WhatsApp Channel, follow dan dapatkan berita terbaru kami di sini
---
Intisari-Online.com -Dua gadis kecil sedang asyik bercanda di tepian teras sebuah kampung yang disebut warganya sebagai sebagai Yudowinangun. Hujan yang turun sejak siang membuat langkah-langkah mungil mereka terasa pendek. Sambil duduk, mereka terus bercerita, dalam bahasa Indonesia yang berlogat Melayu.
Sepintas, mereka tampak seperti anak-anak kampung setempat. Namun sebenarnya, leluhur mereka berasal dari Jawa. Sehari-hari, di rumah mereka berbicara dalam bahasa Indonesia dengan logat Melayu. Tanah Jawa hanya mereka kenal lewat cerita-cerita sekilas dari sang ayah atau mungkin kakeknya, saat mereka habiskan malam sambil menonton televisi.
Orang mengenal Kampung Yudowinangun sebagai basis konsentrasi warga Jawa. Tetapi waktu bergerak dengan cepat. Penduduk kampung itu semakin bertambah banyak. Warga dari etnis lain juga mulai membangun rumah di kampung tersebut. Menurut cerita, Kampung Yudowinangun yang sekarang, luasnya hampir setengah Kota Tanjungpinang.
Membawa bedinde
Ada beberapa pendapat tentang teori kedatangan orang Jawa di tanah Melayu ini. Ada yang menyatakan, kedatangannya di masa penjajahan Belanda, ada yang di masa penjajahan Jepang, atau di masa Kemerdekaan. Masing-masing pendapat punya alasan kuat, mengingat perjalanan sejarah yang berbeda satu sama lain. Bahkan masing-masing arus kedatangan tersebut mempunyai ciri yang unik serta karakteristiknya sendiri.
Mereka yang berpendapat bahwa kedatangan orang Jawa ada di masa penjajahan Belanda, menyatakan peristiwa itu terjadi ketika Kesultanan Melayu Johor Riau Lingga kalah bertempur melawan Belanda yang ditandai dengan gugurnya pejuang Raja Haji Fisabilillah Marhum Teluk Ketapang.
Belanda yang berkuasa segera membuka pos-pos dagang yang didirikan mulai dari Batavia hingga ke Pantai Timur pulau Sumatra, hingga Semenanjung pantai sebelah Barat Melayu khususnya di Bandar Malaka. Khusus di Kepulauan Riau, pos dagang didirikan di Penghujan dan Penuba, dengan maksud untuk meminimalkan gerakan pihak Kesultanan Melayu Johor Riau Lingga.
Keadaan ini terjadi di hampir semua wilayah Nusantara yang terdapat pusat-pusat kekuasaan. Seperti di kerajaan Siak Sri Indrapura, atau di wilayah-wilayah yang kaya timah seperti Pulau Singkep, Karimun (Kundur) yang menjadi wilayah kekuasaan Kesultanan Melayu Riau Lingga, dan di Muntok serta Belinyu yang menjadi daerah kekuasaan Kesultanan Palembang Darussalam.
Pihak Belanda menempatkan personelnya di pos-pos tersebut yang terdiri atas beberapa orang Marsose, Ambtenaar, dan dibantu Opas.Faktor kepentingan pihak Belanda di daerah itu mempengaruhi jumlah personil. Semakin besar jumlah personilnya, menandakan semakin besar kepentingannya.
Orang-orang kulit putih tentu ada di setiap pos, di samping personel dari etnis Jawa yang biasanya dibawa dari Batavia serta etnis lain seperti Manado atau Ambon. Jika diperkirakan tugas mereka akan lama, biasanya mereka akan membawa serta keluarga.
Marsose atau Ambtenaar biasanya juga membawa serta pembantu rumah tangga, disebut bedinde, yang berasal dari etnis Jawa. Alasan mereka biasanya karena sudah memiliki ikatan batin yang kuat dengan bedinde karena sudah mengabdi sejak masa sebelumnya. Selain itu dalam perspektif mereka, orang Jawa mempunyai tingkat kesetiaan, ketelatenan dan ketekunan yang tinggi.
Secara alamiah orang-orang Jawa di daerah perantauan akan mencari kerabat, rekan, hubungan dengan pihak lain yang mempunyai adat kebiasaan, perilaku, bahasa, kesamaan-kesamaan lain.
Komunitas ini menjadi tempat berkeluh kesah, saling bercerita tentang kampung halaman, serta mendapatkan "rasa aman". Selanjutnya pertemuan akan berlanjut dengan pernikahan antar-sesama mereka, serta membentuk sebuah komunitas dengan corak yang sama.
Singgah di daerah kekuasaan Jepang
Pendapat lain menyatakan, pemerintahan militer Jepang yang membawa orang-orang Jawa ketika akan dipekerjakan sebagai romusha. Umumnya mereka berasal dari Jawa Tengah seperti Banyumas, Purworejo, Pacitan, Kutoarjo, Tegal, Wonosari dan Kulon Progo. Jepang merekrut mereka sebagai tenaga kerja dengan berbagai alasan seperti kerik desa, guna membantu perjuangan Jepang yang mengaku saudara tua, cahaya Asia dan penerang, serta pembimbingAsia.
Rombongan romusha dikumpulkan dan diberangkatkan dari beberapa pelabuhan seperti dari Semarang, Cirebon atau Batavia, dengan tujuan antara lain ke Burma. Perjalanan panjang itu tak jarang memakan korban. Selama perjalanan, rombongan romusha selalu menyinggahi daerah-daerah kekuasaan Jepang seperti Pulau Bintan Tanjungpinang, Tanjung Uban, dan daerah Indragiri Sungai di Sungai Guntung dan Siak Sri Indrapura.
Kini di tempat-tempat persinggahan tersebut juga banyak terdapat komunitas orang-orang Jawa. Masih tersisa penggunaan bahasa Jawa dalam pergaulan sehari-hari, walau sudah bercampur baur dengan bahasa Melayu dan bahasa daerah lain. Tak jarang mereka yang menyatu ini selalu memelihara tradisi dari tanah leluhur, sehingga muncul bentuk-bentuk kesenian seperti keroncong, mocopatan, ketoprak, klenengan dan wayangan.
Pada hari besar seperti 17 Agustus atau saat pernikahan warga, kesenian itu akan dipentaskan dengan peralatan yang seadanya. Jangan kaget, kalau pada saat-saat tertentu pula, terdengar musik klenengan khas Jawa yang berkumandang di sudut-sudut rumah di Kampung Jawa.
Kerja keras dan tahan banting
Periode berikutnya adalah ketika Tanjungpinang memasuki masa kemerdekaan dan berstatus daerah Residen yang membawahi beberapa daerah administratif.
Kala itu Tanjungpinang mengalami masa keemasan yang disebut masa dollar. Pada kurun waktu tahun 1950-an hingga 1963 menjelang Konfrontasi Malaysia, dolar Singapura menjadi nilai tukar yang diakui di Kepulauan Riau, di samping Rupiah dan Sen. Kala itu gaji seorang Pegawai Negeri Sipil berkisar antara S$300 hingga S$350. Nilai kurs ini juga mengalami pasang surut. S$1 berharga Rp125 hingga Rp135, menjelang tahun 1963 menjadi S$1 = Rp1.000 padahal Rp1 = 100 sen serta Rp1 = 1000 ketip. Seseorang yang makan sampai kenyang hanya menghabiskan 35 sen saja. Harga sebuah sepeda motor hanya S$250.
Maka, dapat dibayangkan betapa makmurnya mereka ketika itu. Maka berbondong-bondonglah orang-orang dari tanah Jawa mengadu peruntungan dengan motivasi mereka gemerlap dan gemerincingnya dolar Singapura. Biasanya mereka datang karena diajak teman sekampung yang sudah mengadu nasib terlebih dulu. Di perantauan orang-orang ini biasanya siap melakukan pekerjaan apa saja asalkan halal.
Selain itu kedatangan etnis Jawa juga berasal Pegawai Negeri Sipil dan anggota ABRI yang ditugaskan di tempat ini. Gelombang kedatangan yang ketiga ini kebanyakan orang-orang yang berasal dari daerah Pacitan.
Karena mereka pekerja keras dan tahan banting, maka banyak di antara mereka yang hidupnya berhasil dan di kemudian hari orang Jawa asal Pacitan ini mendominasi kehidupan sehari-hari di Tanjungpinang. Lalu muncullah nama-nama tempat yang bercorak Jawa, seperti kampung Yudowinangun, Kampung Wonorejo, Kampung Sidhomukti, Kampung Kerten dan Kampung Sidhodadi.
Begitulah kisah para pendatang Jawa di Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau.